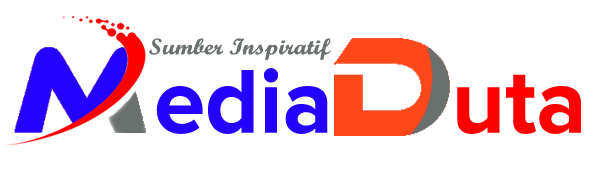Oleh: Irsyam Surahim *)
Ada moral yang sedang diuji. Gelombang korona datang tiba-tiba. Peristiwanya menyeruak di permukaan. Ia berupa tindakan sosial oleh sekelompok yang mengarah pada proses dehumanisasi. Kejadiannya ditandai dengan kekerasan. Kita tahu, kekerasan biasanya membawa luka kemanusiaan yang amat dalam.
Derita kemanusiaan dialami oleh pasien berjangkit korona, di sana orang-orang mulai menciptakan penghindaran diri atas pasien tersebut. Penolakan demi penolakan terjadi. Fenomena ini menemukan bentuk kontradiksi kekerasan. Sosiolog Pierre Bourdiau menamainya dengan istilah “pemaksaan simbolik”. Ada unsur pemaksaan yang menjauhkan seseorang dari kecerdasan merasakan, berempati, dan bersosial.
Kita dipertontonkan tindakan yang jauh melampaui kenyataan sehari-hari kita. Suatu kenyataan yang sesungguhnya tidak lumrah pada masyarakat. Ditandai dengan adanya anggota masyarakat melakukan penolakan jenazah yang positif korona.
Jean Baudrillard, seorang sosiolog posmodern Prancis, di dalam In The Shadow of the Silent Majorities menggunakan istilah hiperealitas. Ia menjelaskan distorsi makna lewat bahasa dalam suatu masyarakat. Baudrillard, melihat kesemuan lebih dianggap nyata daripada kenyataan, dan kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran. Dan masyarakat kita, kadang kala lebih percaya isu ketimbang informasi, rumor dianggap lebih benar daripada kebenaran.
Akhirnya, masyarakat tidak dapat lagi membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara isu dan realitas. Di era digitalisasi saat ini, tidak dapat dimungkiri bahwa bergulirnya informasi ataupun berita membuat gelombang kepanikan pada masyarakat. Sehingga citra virus ini cenderung “destruktif” mewarnai dengan sangat pekat informasi yang diterima masyarakat.
Informasi yang disajikan di berbagai media kontemporer sebagai wujud perang melawan virus ini, justru tak ubahnya melahirkan persoalan sosio-kultural yang berkaitan dengan pengetahuan, nilai dan makna. Yasraf Amir Piliang menamainya fatalitas informasi, yaitu informasi yang membiak tanpa henti dan tanpa terkendali di dalam media telah menggiring individu ke arah “hiperbola”.
Akibatnya, yang terjadi adalah ada kesimpangsiuran kata dan penanda. Pencarian makna dan kebenaran pun menjadi mustahil. Hemat saya melihat bahwa fenomena inilah yang tengah menyelimuti pikiran masyarakat saat ini. Merebaknya isu korona di berbagai belahan dunia dan di tanah air telah menggiring masyarakat ke arah “hiperealitas korona”.
Kampanye-kampanye pembatasan sosial (stay at home, social disatance, phsycal distancing, work from home, lockdown) begitu massif digaungkan telah berperan dalam membentuk hiperealitas ini. Sehingga, betul yang dikatakan Baudrillard bahwa masyarakat lebih memercayai rumor ketimbang kebenaran.
Berita horor korona yang tersebar luas sedikit banyak mulai memengaruhi akal sehat kita. Baudrillard menyebutnya Irasionalitas. Hal itu terjadi lantaran masyarakat telah terkontaminasi ke dalam hiperealitas korona. Ditandai dengan dalih menjaga jarak sosial, menghalangi orang, menyingkirkan individu, mendiskreditkan kelompok, bahkan menindas fisik dan psikologis orang lain, dianggab lebih realistis daripada membuka ruang dialog untuk menemukan kesepahaman bersama.
Denga demikian, bila diamati dari berbagai sudut pandang, hadirnya penolakan pasien berjangkit korona, sesungguhnya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri melainkan manifestasi dari paranoid terhadap korona untuk dihindari sekaligus juga efek dari perubahan frontal korona. Emile Durkheim, seorang sosiolog modern Prancis menamainya dengan istilah “anomie”. Yaitu norma-norma baru belum dirumuskan atau belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat mengalami kehilangan pegangan hidup. Akibatnya hukum atau nilai dan norma di masyarakat mengalami kekacauan.
Saya melihat bahwa, kekuatan-kekuatan horror korona telah melahirkan sikap dehumanisasi. Rasa kemanusiaan telah terkoyak dan semakin terkikis, lantaran kekhawatiran yang belebihan, bahkan tidak sedikit yang berpikiran bahwa korona adalah aib sosial.
Dalam konteks horor korona, kesadaran yang dibangun di dalamnya adalah kesadaran berhadapan dengan fenomena trauma dan derita sosial oleh pasien-pasien berjangkit, yang didalamnya dihasilkan aksi, persepsi dan opini-opini virus. Objek horor yang ditangkap oleh pengalaman masyarakat. Yasraf menyebutnya sebagai halusinasi ruang. Halusinasi yang didapatkan individu dari ruang keterhubungan dan kesalingbergantungan di dunia kehidupannya. Efek boomerangnya ialah masyarakat mulai menciptakan ketakutan akut, yang dibangun di dalam halusinasi teritorial.
Mengakhiri tulisan ini, saya mengutip pernyataan Jhon Gunn dalam kutipan bukunya yang berjudul Violence in Human Society.
Ia mengatakan bahwa bencana krisis kemanusiaan di dalam masyarakat akan terjadi, bila ikatan perekat sosial dalam bentuk cinta, persahabatan, kasih sayang, saling pengertian telah hancur. Bagi Gunn, hancurnya ikatan-ikatan itulah, yang akan menggiring masyarakat ke arah sifat-sifat kebencian atau kemarahan, bahkan kekejaman.
Oleh karenanya, kita yang sadar akan situasi bangsa yang dikepung oleh gelombang ketakutan dan kekerasan, seyogyanya ikut andil mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat, dan mensosialisasikan tindakan-tindakan kecil berupa senantias mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Tentunya dengan bahasa yang meyakinkan masyarakat, dengan cara menunjukan data-data pasien korona yang berhsil sembuh. Dengan begitu persaudaraan dan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat tidak harus tereduksi lantaran citra-citra yang menakutkan. (*)
*) Penulis adalah Irsyam Surahim.
Beralamat di Kel. Lindajang, Suli Barat, Kab .Luwu.
Akun media sosial : ig (IRSYAMSURAHIM_ANDIWAJUANNA),
fb (Irsyam Surahim)
Peserta kelas menulis Rumah Baca Akkitanawa (RBA).